Upaya Sistematis Penghapusan Jejak Dosa Lama, Negara Menolak Terima Fakta
Redaksi
24 Jun 2025
Opini
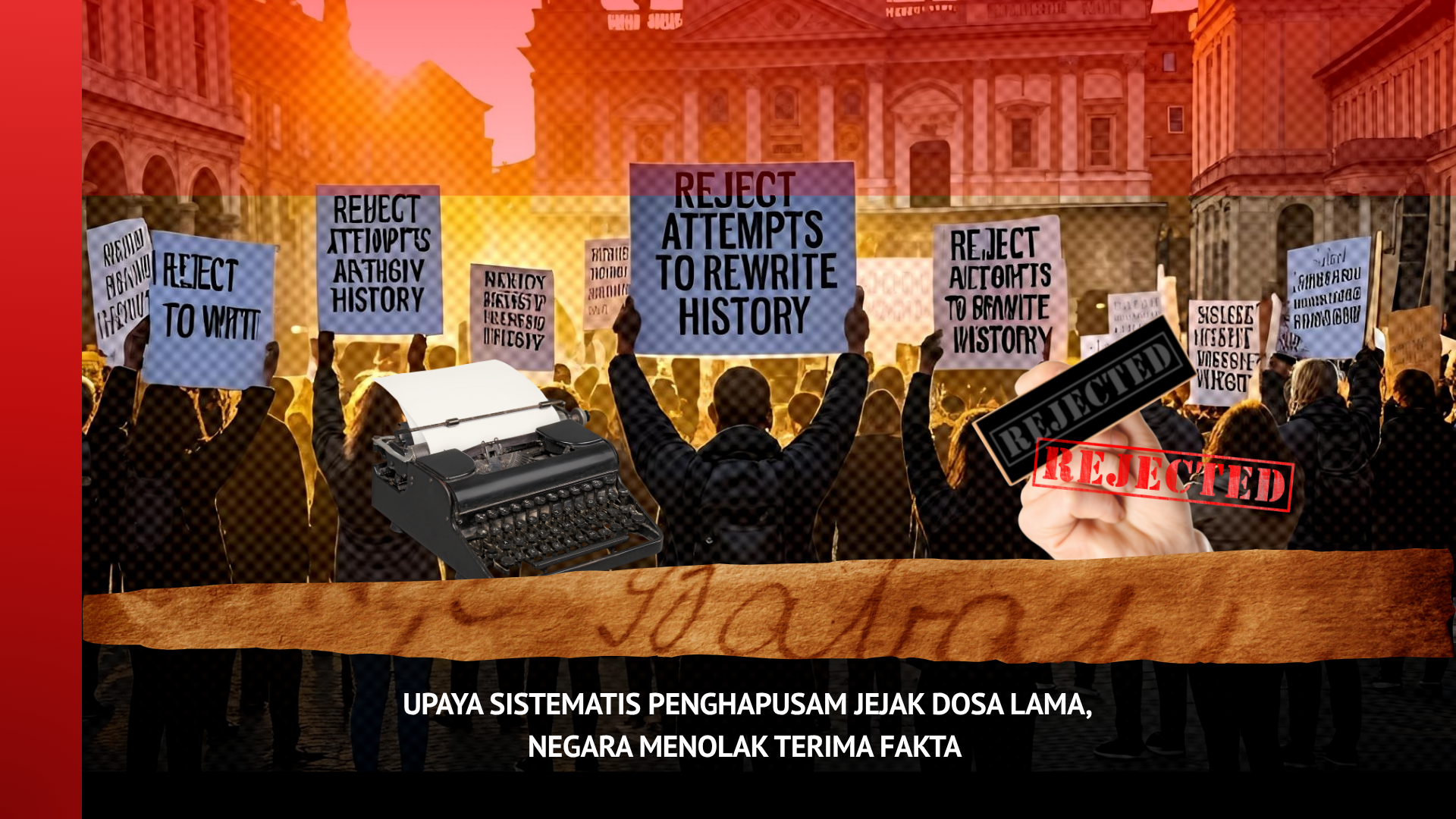
Apa yang terlintas pertama kali saat mendengar pengaburan masa lalu? Sejarah yang disabotase? Kekeliruan masa lalu? Saya kira, secara definitif, pengaburan masa lalu berarti tindakan memutarbalikkan fakta-fakta sejarah atau kejadian di masa lalu, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tujuannya barangkali bisa bermacam-macam: melindungi citra individu tertentu, membentuk narasi baru untuk kepentingan ideologis dan politik, atau menghindari pertanggungjawaban hukum dan moral. Seperti yang kita tahu, penting sekali untuk mempelajari sejarah agar dapat memahami peristiwa di masa lampau supaya kejadian serupa tidak terulang maupun untuk menata masa depan. Akan tetapi, disisi lain, kita juga tahu bahwa sejarah dituliskan oleh sang pemenang, oleh yang berkuasa, oleh yang bertahan.
Lebih-lebih, sejarah menjadi salah satu bentuk pengetahuan yang masuk dalam dunia pendidikan. Pengetahuan sendiri merupakan tema penting dalam ilmu pendidikan karena pengetahuanlah yang didistribusikan oleh guru kepada peserta didik. Tapi sebenarnya, peserta didik seperti apa yang ingin dibentuk oleh penguasa melalui pengaburan masa lalu?
Saat ini, Indonesia tengah diramaikan dengan proyek dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yakni penggarapan penulisan ulang sejarah yang ditargetkan akan dipublikasikan pada tahun 2025 ini. Setidaknya ada 120 sejarawan yang dilibatkan dalam proyek ini, yang mana mereka berkontribusi untuk menuliskan sejarah hingga masa kepresidenan ke-7, Joko Widodo. Kerangka konsep penggarapan penulisan ulang sejarah yang tertanggal 16 Januari 2025 ini memuat sekitar sepuluh jilid buku, mulai dari sejarah awal Indonesia dan asal usul masyarakat Nusantara hingga era Reformasi. Namun, yang kemudian menimbulkan polemik adalah bahwa penulisan ulang sejarah ini dianggap sebagai bentuk pengaburan masa lalu melalui reduksi sejarah. Lebih dari sekadar penulisan ulang, saya melihatnya sebagai upaya pemutihan sejarah. Banyak peristiwa penting yang justru dilupakan. Dilansir dari Tempo.co, gerakan perempuan hingga sederet peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat hilang dari naskah penulisan ulang sejarah tersebut.
Dalam kerangka konsep yang beredar, tertulis bahwa penulisan sejarah ini bertujuan untuk menghasilkan buku sebagai "Sejarah Resmi" dengan orientasi dan kepentingan nasional, guna meningkatkan rasa kebanggaan (nasionalisme) dan cinta tanah air, namun tanpa bersifat nasionalistik. Tapi pertanyaannya: apakah mereduksi sejarah bisa dibenarkan demi kepentingan nasional? Atau, justru ini merupakan bentuk kepentingan pihak-pihak tertentu?
Yang belum lama ini menjadi sorotan adalah dihapusnya tragedi pemerkosaan 1998 dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Tragedi pemerkosaan 1998 merupakan peristiwa pemerkosaan massal terhadap perempuan Indonesia keturunan Tionghoa yang menjadi bagian dari kerusuhan besar pada tahun tersebut. Peristiwa ini menyebabkan puluhan korban perempuan dari berbagai daerah dan latar belakang sosial. Namun alih-alih diakui sebagai bagian kelam dari sejarah bangsa, tragedi ini justru disangkal dan disebut sebagai rumor tanpa bukti oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Padahal, Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah mencatat adanya kasus pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. TGPF dibentuk untuk mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa yang terjadi pada 13–15 Mei 1998. Tim ini terdiri dari unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), LSM, serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
Penyangkalan tersebut tak lain merupakan bentuk upaya revisi sejarah, pembungkaman, dan ketidakadilan terhadap para korban yang hingga kini masih memperjuangkan keadilan. Saya khawatir, jika tragedi serupa terjadi di masa depan, negara akan kembali tutup mata. Bahkan ketika belum terjadi pun, budaya patriarki masih sangat tinggi di negeri ini. Apalagi jika benar-benar terjadi, di mana letak keamanan bagi perempuan? Di mana hak asasi manusia? Ke mana perginya hak-hak masyarakat untuk dilindungi oleh negara?
Lalu, sebenarnya, bukti seperti apa yang mereka inginkan agar peristiwa-peristiwa yang nyaris hilang ini tidak lagi dianggap hanya sebagai rumor tanpa dasar?
Bagi Michel Foucault, seorang filsuf Prancis, pengetahuan adalah wacana yang kebenarannya dilingkupi oleh kekuasaan. Menurutnya, betapapun suci dan luhurnya nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, dalam pemikiran maupun pelaksanaannya, ia tak pernah benar-benar lepas dari campur tangan kekuasaan. Sistem pendidikan dan pengajaran yang kita anut selama ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja tak terkecuali dalam narasi sejarah. Mengesampingkan persoalan masa kini, pengaburan masa lalu sejatinya telah lama terjadi. Salah satu contohnya adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Peristiwa ini memicu penumpasan besar-besaran terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisannya, yang saat itu memiliki pengaruh besar dengan sekitar 20 juta pendukung.
Sejak saat itu, berbagai teori bermunculan mengenai siapa sebenarnya dalang dari peristiwa G30S dari asumsi bahwa Soeharto memanfaatkan situasi untuk mengambil alih kekuasaan, hingga dugaan adanya campur tangan asing. Namun, sebagaimana dikatakan Foucault, sejarah ditulis oleh mereka yang berkuasa. Dan mungkin salah jika saya menyebutnya sebagai ketidakpastian, karena sejak awal, peristiwa ini hingga penulisannya telah direncanakan secara sistematis. Sejarah akhirnya dibentuk sedemikian rupa. Fakta-fakta diputarbalikkan hingga masyarakat percaya akan kekejaman tokoh-tokoh PKI, terutama melalui pemutaran film propaganda di berbagai institusi pendidikan. Kini, memang perlahan-lahan beberapa fakta mulai terungkap. Versi alternatif muncul dari sudut pandang yang sangat berbeda dibanding narasi penguasa narasi yang dulu dipaksakan kepada masyarakat untuk dipercaya.
Namun sayangnya, kebenaran dan fakta yang mulai terbuka itu seolah hanya menjadi percakapan lalu-lalang di ruang publik: terdengar, tetapi mudah dilupakan. Penguasa tidak menunjukkan itikad untuk memperbaiki narasi kosong yang mereka ciptakan.
Kalau begitu, sebenarnya apa tujuan dari penulisan sejarah ini?
Sejarah Indonesia yang dipelajari di sekolah, museum, televisi, dan berbagai media lainnya, pada akhirnya hanya menjadi bagian kecil dari kenyataan yang sesungguhnya. Barangkali pernyataan Ketua Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Susanto Zuhdi, dapat menjadi kunci pembacaan: bahwa sejarah publik melibatkan publik di dalamnya. Tapi sampai sejauh mana batasnya? Untuk kepentingan siapa tujuannya?
Menurutnya, penulisan ini hanya dimaksudkan sebagai referensi pendidikan mengenai sejarah bangsa. Namun jika kita asumsikan, kini fungsi sejarah bukan lagi untuk mengungkap kebenaran, melainkan untuk menundukkan masyarakat. Sejarah menjadi alat untuk menjaga citra kekuasaan, menjadi bentuk pemutihan, sekaligus pelarian negara dari pertanggungjawaban hukum. Atau, jangan-jangan, memang sejak awal sejarah memang dimaksudkan demikian.
Lebih-lebih, sejarah ini adalah bentuk pengetahuan yang akan masuk ke institusi pendidikan. Saya rasa, yang diinginkan pemerintah adalah lahirnya pelajar-pelajar yang percaya pada citra pemerintah yang baik, dan pemerintahan yang bersih tanpa cacat. Sebanyak dan sejelas apapun fakta yang ada, tampaknya tidak akan cukup kuat untuk menghalangi penguasa membungkam dan menyangkal cerita-cerita masa lalu.
Meski demikian, sebagai masyarakat yang merdeka dalam berpikir dan bertindak, bukan berarti kita hanya bisa menerima dan membiarkan hal itu terjadi. Baca, mengerti, bagikan, dan suarakan segala luka yang dihapuskan oleh narasi nasional. Tolak segala bentuk pembungkaman dan penyangkalan yang terus berlangsung.
Jika sejarah semudah itu untuk dihapuskan, maka pertanyaannya: apakah masyarakat benar-benar terlindungi?
Penulis: Noa
Designer: Ayu Atika
Designer: Ayu Atika

